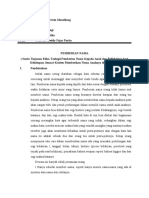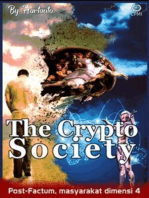Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artikel Tentang Totemisme
Enviado por
Azka Arif MulyantoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artikel Tentang Totemisme
Enviado por
Azka Arif MulyantoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
( Artikel Tentang Totemisme )
Rafi Nurahman M (29) X-11
Totemisme, apa itu?
Written by Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si Sunday, 21 February 2010 02:54
Pernahkah anda mendengar atau mungkin mengetahui bahwa nama-nama hewan sepert igudel (anak kerbau), pedet (anak sapi), kancil, beluk (anak kuda) dan
sebagainya dijadikan nama diri atau nama panggilan seseorang? Bagi orang yang hidup di masyarakat modern, pemberian nama hewan sebagai nama diri tentu sangat aneh sepertinya kok tidak ada lagi nama lain yang lebih baik. Padahal, nama itu sangat penting karena menyangkut identitas, jati diri dan bahkan harga diri seseorang. Islam bahkan mengajarkan agar kita memberi nama yang baik kepada anak keturunan kita. Harapannya adalah agar kelak si anak akan menjadi orang baik, sebaik nama yang disandang. Kendati pujangga kenamaan Inggris William Shakespeare mengatakan What is in a name? (Apalah arti sebuah nama?), menurut saya persoalan nama bukan masalah sepele. Buktinya, orang bisa marah ketika namanya dilecehkan, dicemarkan atau dibuat permainan. Tidak percaya? Silakan mencoba. Saya yakin anda akan berurusan dengan aparat penegak hukum jika orang yang kita lecehkan namanya tidak terima. Lihat saja itu Dr. Chusnul Mariyah, anggota KPU, saat ini sedang berurusan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melecehkan nama baik seseorang.
Kadang-kadang tidak saja nama hewan yang dipakai sebagai nama diri, tetapi juga nama-nama wayang, tanaman (tumbuhan), dan benda tertentu. Saya mempunyai tetangga yang anaknya dipanggil Pedhet. Anehnya, anak tersebut juag menerima saja dengan panggilan tersebut. Bahkan ada juga kerabat saya yang bernama Bagong. Ketika saya masih kecil, saya takut untuk memanggil namanya Pak Bagong. Saya mengira itu bukan nama sebenarnya atau mungkin penggilan akrab bagi orang sebaya. Ternyata saya salah. Bagong adalah nama dia sejak lahir. Padahal, orangnya tinggi besar, sama sekali tidak sama dengan Bagong yang ada dalam
pewayangan, gendhut dan cebol. Saya tidak tahu mengapa orangtuanya memberi nama dia Bagong. Mungkin saja ketika hamil, ibunya sangat suka wayang, khususnya Bagong atau nyidam wayang Bagong. He he! Opo yo ono? Nama Bagong ternyata juga dapat kita temukan di tempat lain. Anda yang sering bepergian Malang-Blitar pasti pernah tahu ada bus yang diberi nama Bagong. Menurut cerita teman saya, nama pemilik bus itu memang Pak Bagong. Kalau begitu, dia pasti orang kaya. Kalau tidak kaya, tidak mungkin dia memiliki beberapa bus. Realitasnya Pak Bagong ini sama sekali tidak sama dengan gambaran wayang Bagong, sebagai salah satu anggotapunokawan, yang merepresentasikan rakyat jelata yang miskin bersama Semar, Petruk, Gareng, dan Limbuk.. Selain Bagong, nama Gareng juga sering kita jumpai di masyarakat. Bahkan di Ponorogo ada penjual nasi tahu lonthong tradisional di tengah kota, langganan saya, bernama mbah Gareng. Nasinya lumayan enak dan bisa membuat kita tuman. Alasan saya semula membeli nasi tahu lonthong di tempat itu karena saya penasaran dengan
nama penjualnya. Seperti apa sih mbah Gareng itu? Jadi tidak karena ingin merasakan seperti apa rasanya nasi tahu lonthongnya. Ternyata orangnya cukup gagah, bahkan lebih gagah ketimbang saya. He he! Anak saya yang paling kecil
pernah nyelethuk orangnya gagah begitu, tapikok bernama mbah Gareng ya Pak? Kalau di pewayangan Gareng kan kecil ya pak? . Tanpa saya duga ternyata mbah Gareng mendengar celethukan anak saya tersebut. Tetapi mbah Gareng, yang ketika itu banyak pembeli yang dilayani, sama sekali tidak marah dan malah senyum-senyum saja mendengar bisik-bisik anak saya itu. Mungkin dia berpikir mengapa dahulu orangtuanya memberi nama dia Gareng. Atau dia berpikir walaupun namanya Gareng yang penting warung nasinya besar dan banyak duitnya daripada namanya mentereng, tapi gak punya duit. He he ! . Lho, kita tidak usah jauh-jauh bahas mbah Gareng yang di Ponorogo atau Pak Bagong yang punya bus jurusan Malang-Blitar. Warga besar Universitas ini kan pernah punya Ketua BEM bernama Obeng ! Dia punya nama asli yang cukup baik. Tetapi di setiap kesempatan, dia selalu mengenalkan diri dengan nama Obeng. Suatu kali saya pernah membuktikan bagaimana dia mengenalkan diri di depan publik. Ternyata benar. Dengan sangat percaya diri dia menyebut namanya Obeng.
Pembaca ! Bagaimana kita menjelaskan fenomena semacam itu dalam sebuah disiplin ilmu tertentu? Para pakar antropologi menyebut fenomena di atas sebagai totemism atau
totemisme. Mungkin tidak banyak orang mengenal istilah totemism atau totemisme, apalagi memahami artinya. Sebab, ia adalah istilah teknis dalam antropologi. Menurut The New Grolier Webster International Dictionary of the English LanguageVolume II (1974: 1040), totemism adalah The practice of having totems; the system of tribal division according to totems; belief in relationships between people or groups of people and totems. Totem sendiri diartikan sebagai Among primitive culture, an object or thing in nature, often an animal, assumed as the token or emblem of a clan, family, or related group; a representation of such an object serving as a distinctive mark of the clan or group. Jika diartikan secara bebas totemisme adalah praktik penggunaan nama-nama hewan, tanaman atau benda tertentu sebagai nama diri karena adanya pandangan tentang hubungan personal yang bersifat sakral antara individu dalam masyarakat primitif dengan hewan, benda, dan tumbuhan tertentu di sekitarnya. Jadi kata kuncinya adalah totemisme terjadi di masyarakat primitif atau tradisional, di mana orang mempercayai bahwa hewan, tumbuhan, atau benda tertentu memiliki nilai sakral. Oleh karena itu, nama-nama hewan, tumbuhan dan benda-benda tertentu seperti pedhet, pecok, kancil, gareng dan sebagainya kita jumpai untuk dijadikan nama diri agar pemakai nama tersebut selamat, banyak rezeki, hidupnya tenteram dan lain sebagainya. Belakangan fenomena totemisme tidak saja dikaji oleh para ahli atau peminat studi antropologi, tetapi juga antropolinguistik dan sosiolinguistik. Dua kelompok pengkaji terakhir berangkat dari tesis SapirWhorf, dua peneliti bahasa dan budaya yang
menawarkan hipotesis language shapes culture, yakni bahasa dapat menentukan sosok kebudayaan. Cara berpikir adalah bagian dari kebudayaan. Jadi bahasa atau kata dapat membentuk sosok pikiran kita. Hipotesis Sapir-Whorf berbeda dengan pandangan para teoretisi sebelumnya yang berasumsi bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Jadi bahasa terbentuk setelah pikiran ada, sebuah asumsi yang terjadi bagi kebanyakan orang. Dapat diilustrasikan pula bagaimana jika seseorang diberi label maling di sebuah masyarakat. Kata maling tersebut pasti melahirkan sederet definisi atau pandangan tentang orang tersebut, seperti jahat, jelek, dihindari, diwaspadai dan sebagainya. Dengan kata lain, kata maling sangat menyiksa dia. Dengan demikian, bahasa benarbenar telah menjadi penjara bagi orang itu. Language is a real prison. Dengan menggunakan hipotesis Sapir-Whorf tersebut, maka jika Pedhet dipakai sebagai nama diri seseorang kita bisa membayangkan atau berpikir sosok manusia atau orang macam apa pengguna nama pedhet itu. Begitu juga seterusnya untuk nama-nama tumbuhan, atau benda-benda tertentu yang lain. Karena totemisme itu umumnya terjadi di masyarakat primitif atau tradisional, kendati istilah primitif atau tradisional didefinisikan secara berbeda-beda oleh para sosiolog, maka untuk membayangkan sosok pikiran macam apa yang terjadi pada pengguna totemisme tersebut tampaknya kita perlu berempati dulu dengan anggota masyarakat primitif. Para penggagas aliran fenomenologi menganjurkan untuk memahami dunia batin seseorang kita harus belajar berempati dengan seseorang tersebut, kendati kita
tidak harus menjadi dia. Sebab, meminjam istilah Brian Fay dalam Contemporary Philosophy of Social Science (1998: 9)We dont have to be one to know one. Artinya, untuk memahami seseorang, kita tidak harus menjadi orang itu, dan memang tidak mungkin. Tetapi ketika saya sedang mencoba memahami fenomena totemisme secara komprehensif, tiba-tiba dari benak saya muncul pkiran apa benar totemisme itu hanya terjadi di masyarakat primitif atau tradisional, seperti di daerah-daerah pedesaan di Indonesia. Sebab, tidakkah di masyarakat yang super maju seperti Amerika fenomena totemisme juga terjadi? Banyak orang Barat bernama Mr. Hill, Mr. Can, Mr. Wood dan sebagainya. Bahkan, bukankah Presiden Amerika Serikat saat ini bernama Bush, yang dalam bahasa Indonesia berarti semak? Dan, semak adalah nama tumbuhan. Lalu dengan demikian apa kita bisa menyebut Amerika sebagai masyarakat primitif atau tradisional? Kalau begitu pembahasan tentang totemisme memang tidak akan selesai dalam tulisanKolom ini. Lebih baik kita bahas secara tuntas dalam diskusi di matakuliah antropologi, antropolinguistik atau sosiolinguistik. Atau, di lain kesempatan jika waktu memungkinkan.
( Sumber : http://mudjiarahardjo.com/artikel/113-totemisme-apa-itu.html )
Você também pode gostar
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaNo EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (16)
- Laporan StulapDocumento23 páginasLaporan Stulaptri ekowarnoAinda não há avaliações
- Nyinau Tembung Ora IlokDocumento9 páginasNyinau Tembung Ora IlokMas GambirAinda não há avaliações
- Bahasa Sebagai Anugerah TuhanDocumento15 páginasBahasa Sebagai Anugerah TuhanRestu KristianzegaAinda não há avaliações
- Proses PenamaanDocumento1 páginaProses PenamaananikAinda não há avaliações
- Bab 2 Manusia Buddha 2Documento17 páginasBab 2 Manusia Buddha 2Tiffany WinarsoAinda não há avaliações
- Agama 2Documento15 páginasAgama 2Jonathan MAinda não há avaliações
- Bahasa Sebagai Faktor Penyebab Utama Terbangunnya Peradaban by Fadly BahariDocumento13 páginasBahasa Sebagai Faktor Penyebab Utama Terbangunnya Peradaban by Fadly BahariFadly BahariAinda não há avaliações
- Tugas 2. Makalah Filsafat Ilmu-Yessica Chrisna DewiDocumento11 páginasTugas 2. Makalah Filsafat Ilmu-Yessica Chrisna Dewihendri antoniAinda não há avaliações
- Esai Tentang Perbedaan Manusia Dan HewanDocumento10 páginasEsai Tentang Perbedaan Manusia Dan HewanPK IPNU IPPNU SABILUL HUDAAinda não há avaliações
- Aku Cinta JokowiDocumento4 páginasAku Cinta JokowiAl FaAinda não há avaliações
- Seminar Etika HendraDocumento12 páginasSeminar Etika HendraNella E SiraitAinda não há avaliações
- 5 Pilar KejawenDocumento3 páginas5 Pilar Kejawensururi arumbaniAinda não há avaliações
- HBEC3603Documento9 páginasHBEC3603Deena ZackAinda não há avaliações
- Sejarah BahasaDocumento5 páginasSejarah BahasaMeisyarifah HalwaAinda não há avaliações
- Roni Filsafat TugasDocumento3 páginasRoni Filsafat TugasRoNy Efendi ManullangAinda não há avaliações
- Uas Filsafat NusantaraDocumento5 páginasUas Filsafat NusantaraKarisma Nur AiniAinda não há avaliações
- Kajian Bahasa Materi 1Documento7 páginasKajian Bahasa Materi 1Fadelina Wizola DivaAinda não há avaliações
- Sangkamadeha - Pohon Kehidupan Orang BatakDocumento70 páginasSangkamadeha - Pohon Kehidupan Orang Batakericson.ltbAinda não há avaliações
- Ujian Akhir Semester Filsafat UmumDocumento4 páginasUjian Akhir Semester Filsafat UmumCici StephaniAinda não há avaliações
- Materi DongengDocumento7 páginasMateri DongengAep SaepudinAinda não há avaliações
- Asal Usul BahasaDocumento14 páginasAsal Usul BahasaGuest Number OneAinda não há avaliações
- Contoh Kasus OntologiDocumento4 páginasContoh Kasus OntologiFionna Pohan100% (1)
- Arti NamaDocumento6 páginasArti NamaKusama NowakiAinda não há avaliações
- ANS Kel.3Documento9 páginasANS Kel.3jaka putraAinda não há avaliações
- Artikel Jurnal SosiolinguistikDocumento7 páginasArtikel Jurnal SosiolinguistikZulfikar AlamsyahAinda não há avaliações
- UntitledDocumento31 páginasUntitledCindy LorensaAinda não há avaliações
- Manusia Purba. AdiDocumento26 páginasManusia Purba. AdiHandi FerdiansahAinda não há avaliações
- Esai Kelompok 1Documento7 páginasEsai Kelompok 1Aw AdivaraAinda não há avaliações
- Saa K2Documento11 páginasSaa K2AbnerAinda não há avaliações
- Sanggah KemulanDocumento21 páginasSanggah KemulanGdWijanaAinda não há avaliações
- Filsafat Seni JakobDocumento8 páginasFilsafat Seni Jakobsoft cousticAinda não há avaliações
- JURNALDocumento10 páginasJURNALMuhammad Fahmi Ad-DhaifAinda não há avaliações
- Tujuh Unsur KebudayaanDocumento4 páginasTujuh Unsur KebudayaanYasfi Maziya Mufida0% (1)
- Sanggah KemulanDocumento19 páginasSanggah KemulanindramahayaniAinda não há avaliações
- Subtugasan 2 KKP BMM3111Documento47 páginasSubtugasan 2 KKP BMM3111Autdrey YnaAinda não há avaliações
- Bab I PendahuluanDocumento15 páginasBab I PendahuluancharolAinda não há avaliações
- Alam Pikir YunaniDocumento2 páginasAlam Pikir Yunanianto kammi100% (2)
- Bab IiDocumento18 páginasBab IiDewa Putu TagelAinda não há avaliações
- Entitas PerempuanDocumento232 páginasEntitas PerempuanIbnu PurwantoAinda não há avaliações
- Bab 1 Asal-Usul BahasaDocumento14 páginasBab 1 Asal-Usul BahasaBayu SilaartaAinda não há avaliações
- Tugas Konseling Lintas Budaya 1Documento2 páginasTugas Konseling Lintas Budaya 1Emitha Bulan AjizzahAinda não há avaliações
- Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Un PDFDocumento159 páginasSemiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Un PDFAgus SupratmanAinda não há avaliações
- Wewaler (Pamali)Documento3 páginasWewaler (Pamali)sabrinaphotoarchivesAinda não há avaliações
- Nurmila Awalia 6B-LB IIIDocumento3 páginasNurmila Awalia 6B-LB IIItofu tofuAinda não há avaliações
- Makalah Agama IslamDocumento14 páginasMakalah Agama IslamImaduddin SalimAinda não há avaliações
- Makalah Hakekat ManusiaDocumento13 páginasMakalah Hakekat ManusiaalydyaAinda não há avaliações
- Pengertian DongengDocumento13 páginasPengertian DongengAgus CahyadinAinda não há avaliações
- Pola-Pola Pikir (Kajian Antropologi)Documento21 páginasPola-Pola Pikir (Kajian Antropologi)Hadi SaputraAinda não há avaliações
- Pemikiran Agnostik (Freethinker)Documento32 páginasPemikiran Agnostik (Freethinker)Ja'far AgyoAinda não há avaliações
- Makalah FolklorDocumento7 páginasMakalah FolklorrizanaAinda não há avaliações
- Tugas Arti ManusiaDocumento1 páginaTugas Arti ManusiaAgus IrawanAinda não há avaliações
- Makalah Bahasa Sunda Lutung KasarungDocumento14 páginasMakalah Bahasa Sunda Lutung KasarungRingga Abdurrahman100% (1)
- Contoh Script Podluck PodcastDocumento4 páginasContoh Script Podluck Podcastakuayam.idAinda não há avaliações
- Materi Sosiologi EkonomiDocumento111 páginasMateri Sosiologi EkonomiTeuku RaziansyahAinda não há avaliações
- Tugas 5Documento3 páginasTugas 5nibsaya sayaAinda não há avaliações
- Tabula Rasa - Islam PerspektifDocumento2 páginasTabula Rasa - Islam Perspektifardian majidAinda não há avaliações
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganNo EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (10)